Konon, ada empat jalan menuju “kesejatian”: sains, filsafat, sastra, dan agama. Para pencari kesejatian sejak berabad-abad silam memilih jalan setapak mereka masing-masing. Ada yang berhasil menemukan “kebenaran”, tapi banyak pula yang tak kunjung memperoleh apa yang mereka cari. Alih-alih menemukan kebenaran, jalan yang mereka ambil justru membuat mereka tersesat.
Dalam Sang Raja Jin (Kayla, 2008), novel karya Irving Karchmar, kita bisa merasakan jejak keempat jalan setapak itu, terutama dua jalan terakhir. Dalam pandangan saya, Sang Raja Jin adalah sebuah karya sastra yang berupaya menyingkap hakikat kesejatian melalui pendekatan tasawuf.
Kisah bergulir melalui penuturan sang narator, Ishaq, seorang murid tarekat yang semula adalah mahasiswa filsafat yang serius dan “rasional”. Sosok Syekh Haadi, sang mursyid tarekat, merupakan tokoh dominan yang kerap mewejang murid-muridnya tentang berbagai rahasia semesta dan kearifan tersembunyi. Ada pula Profesor Solomon, seorang ilmuwan Yahudi, dan putrinya yang penuh cinta, Rebecca; seorang tentara Israel yang “menemukan takdir” dengan cara yang ganjil, Kapten Aaron; sepasang saudara, Ali dan Rami, yang rela “meniadakan diri” untuk sesuatu yang lebih penting dari diri pribadi dengan terjun ke sumur api; Amenukal, seorang kepala suku pengembara yang ternyata sufi bermaqam tinggi; serta tokoh faqir misterius yang “sakti” jelmaan sesosok jin bernama Ornias. Sementara itu, yang dimaksud sebagai Raja Jin dalam novel ini adalah Baalzebul, penghulu kaum jin yang tengah berseteru dengan kelompok jin kafir yang dipimpin Ifrit.
Irving menggunakan novelnya ini sebagai medium penggambaran pencarian kesejatian melalui tokoh-tokohnya yang beraneka latar, tapi dipertemukan “takdir” yang menggiring mereka ke satu titik yang sama: “jalan cinta”—tentunya setelah melalui berbagai pergulatan.
Sebagai sebuah novel, Sang Raja Jin mengambil bentuk yang sederhana, tapi mengandung isi yang dalam. Ia indah, sekaligus bermakna. Dulce et utile. Novel yang diterjemahkan dan disunting dengan bagus ini mengandung kisah yang menarik sehingga membuatnya enak dibaca, sekaligus mengajak pembacanya “merenung”. Dan saya kira, itulah inti novel ini: perenungan tentang hakikat kehidupan dan penciptaan.
Ada banyak hal yang menarik dibahas lebih lanjut dari novel ini, tapi yang paling menarik buat saya adalah yang berkaitan dengan kematian dan cinta. Berkaitan dengan dua hal tersebut, izinkan saya mengutip beberapa kalimat yang menggelitik dalam novel ini:
Kematian adalah salah satu anugerah terlembut dari Tuhan. Kematian memisahkan orang dari kegembiraan dan kesedihan sementara, yang hanya setetes belaka bagi jiwa. …di balik kematian ini terbentang Samudra Cahaya… (hal. 33)
…kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kalian takut padanya. Jiwa kalian takut ketika memikirkan kematian. Tetapi seorang Sufi tak meminta apa pun, dan tak takut pada apa pun, sebab ia telah memasrahkan hidupnya dan menyerahkan segala yang dimilikinya kepada Tuhan. (hal. 34)
Kami berjuang untuk menaklukkan ego dalam pikiran dan perbuatan kami, dan berusaha bersyukur atas anugerah Allah dengan menghambakan diri dalam banyak pelayanan. (hal. 113)
Ketika Allah menciptakan umat manusia, semuanya mengatakan mencintai-Nya. Maka Dia kemudian menciptakan kesenangan-kesenangan duniawi, dan sembilan per sepuluh dari mereka segera meninggalkan-Nya, sehingga yang tersisa hanya sepersepuluhnya. Kemudian Allah menciptakan kemegahan dan kenikmatan Surga, dan sembilan per sepuluh dari sepersepuluh yang tersisa itu meninggalkan-Nya. Lalu Allah menimpakan bencana dan kesedihan kepada sepersepuluh yang tersisa itu. Dan sembilan per sepuluh dari sepersepuluh yang tersisa itu juga melarikan diri dari-Nya. … Manusia-manusia yang menjauh dari-Nya itu terombang-ambing antara kesenangan, harapan, dan putus asa. Tapi, mereka yang tetap bertahan, yakni sepersepuluh dari sepersepuluh dari sepersepuluh yang tersisa, adalah manusia-manusia pilihan. Mereka tidak menginginkan dunia, tidak mengejar surga, dan tidak melarikan diri dari derita. Hanya Allah semata yang mereka inginkan, dan walaupun mereka menerima penderitaan dan cobaan yang bisa membuat gunung-gunung gemetar ketakutan, mereka tidak meninggalkan cinta dan kepasrahan kepada-Nya. Mereka adalah hamba Allah yang sejati, pencinta Allah yang sesungguhnya. (hal. 114-115).
Mengikuti jalan cinta harus menjadi hamba sejati, harus melayani Tuhan dan segenap makhluk-Nya, agar mereka bisa menemukan jalan yang benar. (hal. 115)
… Jika datang kepadamu orang yang sakit karena berpisah dari-Ku, sembuhkanlah dia. Atau bila karena melarikan diri dari-Ku, carilah dia. Atau jika karena takut kepada-Ku, yakinkanlah dia. Lalu beri bantuan kepadanya, atau kalau kau bertemu dengan orang yang mencari-Ku, bantulah dia mendekati-Ku. Atau jika dia amat membutuhkan rahmat-Ku, bantulah dia. Atau jika dia berharap kasih sayang-Ku, ingatkanlah dia. Dan jika dia tersesat, carilah dia. Sebab engkau telah ditakdirkan untuk membantu-Ku, dan engkau telah kuangkat untuk melayani-Ku. (hal. 115)
Kebanyakan manusia tidak melihat bahwa dalam kesadaran akan cinta tersembunyi kesadaran akan Tuhan… (hal. 154)
Ketahuilah… cinta adalah dasar dan prinsip dari jalan menuju Tuhan. Segala keadaan dan maqam adalah tahapan-tahapan cinta, yang tak akan bisa dihancurkan selama Jalan Cinta itu ada. (hal. 282)
… ketika Tuhan menyuruh mereka melihat alam semesta yang diciptakan-Nya, mereka tak melihat hal-hal yang lebih berharga ketimbang diri mereka sendiri, dan karenanya mereka dipenuhi kebanggan dan kesombongan… Tubuh sujud dalam shalat, dan jiwa meraih cinta, ruh sampai ke kedekatan dengan Tuhan, sedangkan hati mendapat kedamaian dalam persatuan dengan Allah… Cinta tak bisa dijelaskan. Penjelasan tentang cinta bukanlah cinta, karena cinta melampaui kata-kata… cinta adalah anugerah ilahi. Ia tidak dapat direbut, juga tak bisa dilawan. (hal. 283)
Dalam novel ini dikisahkan tokoh-tokoh yang gagal mengatasi dosa-dosa maut dalam diri—seven deadly sins: lust (syahwat), anger (amarah), envy (dengki), gluttony (rakus), greed (tamak), sloth (malas), pride (sombong)—menemui akhir yang tragis, antara lain sosok Afarnou (anak Amenukal yang menemui kematian sia-sia di gurun pasir karena ketamakan, kemalasan, dan kesombongannya) serta Ifrit yang menutup diri dari kebenaran dan rahmat Allah akibat kemarahan, kedengkian dan kesombongannya sehingga harus mengalami “hidup” yang pedih.
Sementara itu, tokoh-tokoh yang dengan penuh keikhlasan bersedia menghadapi kematian dalam menjalankan “tugas kehidupan” dengan berkelana tanpa tahu takdir apa yang bakal menjemput, justru selamat dan menemukan “jalan Tuhan”.
Menarik juga menyimak bahwa tokoh-tokoh yang berakhir baik tak selalu baik dan sempurna. Tidak hitam putih. Profesor Solomon adalah orang yang ragu yang baru tercerahkan pada usia tua. Ornias adalah jin maling dan pembunuh yang bertobat dan kemudian berhasil meningkatkan semesta dirinya. Sungguh, yang luar biasa bukanlah yang tak pernah jatuh, melainkan yang bisa bangkit dari kejatuhan. Mereka berhasil keluar dari “penjara diri” dengan mengatasi segala tarikan nafsu diri pribadi, menyatu dengan kehendak Tuhan melalui pengutamaan pelayanan terhadap sesama makhluk daripada kenyamanan pribadi, dan akhirnya meraih cinta, abadi dalam cinta.
Seperti kata Rumi, “Jika kau ingin mengetahui dirimu yang sejati, keluarlah dari dirimu/Tinggalkan selokan dan mengalirlah menuju Sungai.” Atau seperti yang ditulis penyair sufi lainnya, “Ketahuilah bahwa ketika kau belajar kehilangan dirimu, kau akan mencapai Yang Terkasih…” Selaras pula dengan ajaran Lao Tze dalam Tao Te Ching, “Yang mengalahkan diri sendiri disebut kuat… Yang mati tapi tak binasa disebut panjang umurnya.”
Dan, seperti yang sedikit banyak tergambar dalam novel ini, jalan menuju kesejatian itu jelas tak gampang dilalui. Sungguh tak mudah menaklukkan diri sendiri. Namun demikian, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung.
Resensi oleh Anton Kurnia, orang awam yang suka membaca dan menulis.




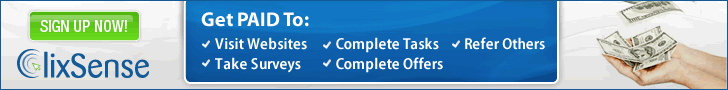






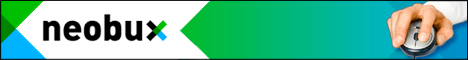


0 komentar:
Posting Komentar